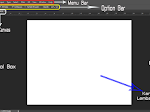Oleh: Kadarisman
Presidium Majelis Daerah KAHMI Tabalong
Peribadatan dalam agama merupakan wilayah otonom dan bersifat asasi bagi penganut agama itu sendiri. Otonomi agama dalam peribadatannya diakui dan tidak dicampuri negara.
Itu sebab negara kemudian memberikan jaminan bahwa kebebasan menjalankan peribadatan dan beragama termaktub dalam konstitusi dasar negara Republik Indonesia.
Landasan kuat itu mesti dipahami dan dimengerti oleh penyelenggara pemerintahan. Pemerintah merupakan perpanjangan amanat negara yang lahir atas dasar kehendak rakyat.
Pemerintah jangan tergelincir menggunakan kekuasaan yang rakyat titipkan untuk memasuki wilayah private peribadatan yang sakral atas nama regulator.
Hal itu yang terjadi Pekalongan. Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid sempat menolak memberikan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk kegiatan salat Idul Fitri sebagian umat Islam yang merayakannya pada 21 April 2023.
Alasan penolakan walikota karena pemerintah pusat belum menetapkan 1 Syawal 1444 H. Menurutnya Pemkot Pekalongan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menggelar salat Ied harus sama dengan keputusan pemerintah, sehingga Lapangan Mataram yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak diperkenankan digunakan umat muslim yang merayakan salat Ied pada 21 April 2023.
Interpretasi yang dangkal tersebut dalam menjalankan pemerintahan di daerah menunjukkan gagal pikir dan kegagalan dalam memahami konsep bernegara oleh seorang kepala daerah.
Kepala daerah harus mampu memahami dirinya sebagai penyelenggara dari konstitusi, bukan sebagai suporter salah satu kelompok di dalam agama.
Pemerintah harus berdiri di tengah-tengah dan tidak memihak salah satu dari keyakinan ritual peribadatan umat dalam menjalankan agamanya, lalu menjadi pemerintah yang suka mempersekusi rakyatnya sendiri.
Sebagai pemegang pemerintahan, kepala daerah mesti memposisikan dirinya sebagai pemberi layanan kepada parapihak di dalam menjalankan peribadatan yang diyakininya. Bukan sebaliknya menjadi pemain dari salah satu pihak.
Walikota Pekalongan, telah gagal memahami konsep penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakatnya.
Kendati polemik penggunaan Lapangan Mataram itu kemudian direvisi, yang semula tidak diizinkan menjadi diizinkan, tetap saja tidak dapat menjernihkan bahwa paham rezimisasi beragama tumbuh di dalam mental sebagain kepala daerah dan birokratnya.
Mental rezimisasi beragama dapat memicu tumbuhnya intoleransi di kalangan masyarakat horizontal dan masyarakat awam. Masyarakat akan terpecah bukan karena perbedaan tetapi karena tersulut kebijakan yang tidak tepat oleh penguasa di daerah.
Kepala daerah tidak boleh bermain-main dalam konteks yang dapat melabelisasi pemerintah dalam peribadatan agama. Jika itu terjadi sangat berpotensi menyulut konflik turunan dan perpecahan.
Kepala daerah mesti kembali kepada tugas-tugas kenegaraan dan menjalankan kekuasaan yang berdiri di atas semua golongan, menjadi pelayan bagi semua kalangan, menjadi fasilitator kepada semua rakyat.
Langkah latah pemerintah acap kali didorong oleh kurangnya pemahaman dalam memandang perbedaan.
Perbedaan selama ini dipandang sebagai pemicu rusaknya ketertiban dan kemananan, padahal perbedaan harus dipandang sebagaimana Tuhan menjadikannya sebagai fitrah kehidupan dan sebagai rahmat bagi alam.
Sejatinya bukan karena berbeda konflik terjadi, tetapi karena tidak hadirnya penghormatan atas adanya perbedaan. Konflik dapat ditiadakan, tetapi perbedaan adalah titah Tuhan.
Walikota Pekalongan gagalnya di konsep ini, sehingga dia khilaf dan latah. Tetapi itu cepat disadarinya dan cepat pula dia memperbaikinya.
Namun melihat caranya untuk sadar negitu cepat, maka perlu diapresiasi. Karena menurunkan ego kekuasaan itu pun sesuatu yang tidak mudah. Walikota Pekalongan mampu melakukannya.
Apa yang terjadi di Pekalongan dapat menjadi cermin bagi di Banua. Menjadi kepala daerah jangan latah.*